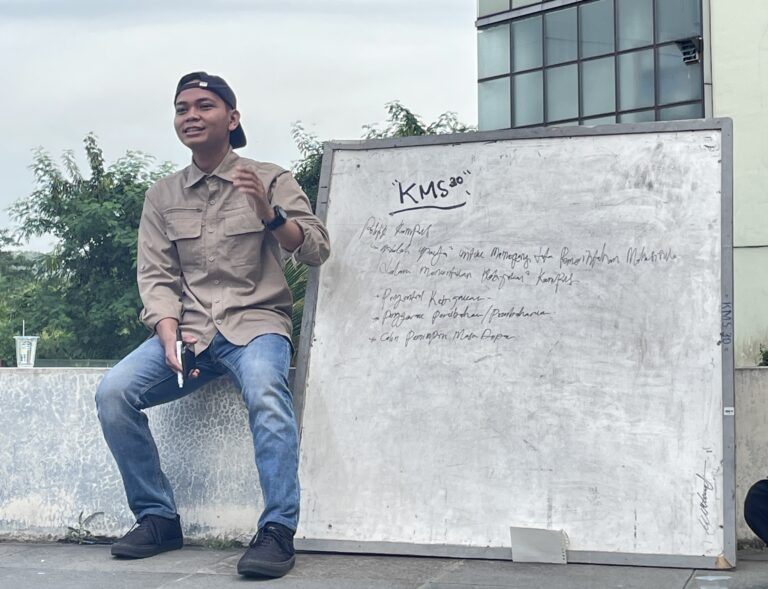OPINI
Oleh: Aldi Agus Setiawan
Jakarta kembali dikepung banjir. Pada awal Juli 2025, curah hujan ekstrem melebihi 100 mm/hari yang terjadi di kawasan Bogor–Puncak dan Jakarta, bahkan berdasarkan data BMKG dan BPBD DKI Jakarta, curah hujan di kawasan hulu mencapai 150 mm pada 5–6 Juli 2025, jauh di atas ambang normal dan memicu banjir di 53 titik di ibu kota dengan ketinggian genangan 30 cm hingga 2,7 meter. Kondisi ini diperparah oleh perubahan tata ruang kawasan Puncak Bogor yang masif, di mana area resapan berubah menjadi kawasan wisata dan pemukiman
Peristiwa ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan merupakan hasil dari kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan ekologi dan tata ruang kota yang berkelanjutan. Masalah alih fungsi lahan di kawasan hulu, penurunan daya resap, eksploitasi air tanah, serta lemahnya sistem pengelolaan DAS Ciliwung merupakan faktor kunci yang menyebabkan banjir Jakarta kian sulit dikendalikan.
Selain itu, riset yang dilakukan oleh Abidin et al. dalam Land Subsidence of Jakarta and its Relation to Urban Development (2011), menyatakan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah mencapai 2–15 cm/tahun di beberapa wilayah Jakarta, dengan 40% wilayah kini berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini mempersulit air hujan maupun limpasan dari hulu untuk dialirkan ke laut secara alami, khususnya saat terjadi pasang maksimum.
Ketimpangan tata ruang juga menjadi penyebab krusial. RTH Jakarta hanya tersisa sekitar 9,98% dari total luas wilayah, jauh di bawah ketentuan minimal 30% dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Alih fungsi lahan masif untuk kepentingan komersial menyebabkan minimnya ruang resapan air di dalam kota.
Seperti yang didefinisikan oleh Brundtland Commission dalam Our Common Future (1987), bahwa keberlanjutan dalam konteks perkotaan diartikan sebagai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat saat ini dan masa depan. Namun, di Jakarta, keberlanjutan justru dipinggirkan. Pembangunan infrastruktur besar seperti Giant Sea Wall (National Capital Integrated Coastal Development) lebih diutamakan dibanding upaya restorasi ekologis di kawasan hulu dan bantaran sungai.
Pusat riset UN ESCAP melalui Expert Group Meeting on Asia-Pasific’s Sinking Cities (2024) menyebutkan bahwa kota-kota pesisir di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Jakarta, rentan tenggelam bukan hanya akibat perubahan iklim, tetapi juga karena tata kelola yang abai terhadap prinsip ekosistem dan keberlanjutan—khususnya eksploitasi air tanah dan hilangnya ekosistem pantai.
Yang juga perlu digaris bawahi ialah bahwa banjir membawa dampak serius bagi kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam seminar naional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (2024), kerugian ekonomi banjir Jakarta diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun. Selain itu, ancaman kesehatan meningkat akibat paparan air limbah, penyakit berbasis air seperti diare dan leptospirosis, serta gangguan psikososial bagi warga yang terdampak.
Bencana ini juga mengganggu produktivitas ekonomi dan menghambat aktivitas sosial masyarakat urban. Studi Pelling & Blackburn dalam buku Megacities and The Coast (2013) menegaskan bahwa ketahanan perkotaan tidak bisa dicapai tanpa membangun harmoni antara ruang kota dan ekosistemnya.
Menghadapi persoalan ini, sudah saatnya Jakarta melakukan koreksi total terhadap paradigma pembangunan yang selama ini dijalankan. Pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan proyek betonisasi sungai atau bendungan raksasa, melainkan harus menyentuh akar persoalan: perbaikan tata ruang, pengendalian kawasan hulu, serta pembenahan sistem drainase kota.
Restorasi kawasan hulu menjadi langkah prioritas. Reboisasi dan pengendalian alih fungsi lahan di Bogor dan Puncak mutlak dilakukan untuk mengembalikan daya serap kawasan hulu. Pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Pemprov Jawa Barat harus duduk bersama menyusun kebijakan pengendalian kawasan hulu secara serius, tanpa kompromi terhadap kepentingan komersial.
Di dalam kota, revitalisasi ruang terbuka hijau harus dipercepat. Lahan-lahan kosong milik pemerintah bisa diubah menjadi taman kota, taman vertikal, atau kolam retensi alami. Selain berfungsi sebagai resapan air, keberadaan ruang terbuka hijau juga penting untuk kesehatan psikologis dan kualitas hidup warga kota.
Pengendalian eksploitasi air tanah juga harus ditegakkan. Pemprov DKI bersama kementerian terkait perlu memperluas jaringan air bersih PDAM dan melakukan moratorium izin sumur bor, khususnya bagi industri dan bangunan komersial.
Yang tak kalah penting, edukasi dan pelibatan warga dalam pengelolaan lingkungan juga harus diperkuat dengan penerapan nature-based solution (NbS). Kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan membatasi aktivitas yang merusak kawasan resapan harus dibangun sejak dini. Program kampung hijau, bank sampah, dan urban farming bisa menjadi gerakan kolektif yang memperkuat ketahanan lingkungan berbasis komunitas.
Kembali lagi, banjir Jakarta awal Juli 2025 bukanlah takdir atau semata bencana hidrometeorologis, tetapi manifestasi dari rusaknya tata kelola lingkungan dan tata ruang perkotaan yang abai terhadap prinsip keberlanjutan dan keputusan-keputusan keliru yang dilakukan bertahun-tahun. Jika terus dibiarkan, Jakarta bukan hanya akan tenggelam secara fisik, tetapi juga secara peradaban. Kita tidak bisa lagi membiarkan keberlanjutan menjadi jargon kosong di atas kertas perencanaan.
Kejadian ini menjadi alarm bahwa pembangunan Jakarta perlu mengedepankan pendekatan restoratif berbasis ekosistem dan keberlanjutan sosial, bukan sekadar solusi struktural teknis.
Keberlanjutan harus kembali menjadi fondasi utama dalam kebijakan dan perencanaan kota. Kota ini hanya bisa bertahan jika mampu membangun harmoni antara manusia, ruang, dan lingkungan. Tanpa itu, Jakarta akan terus berada dalam siklus bencana ekologis yang makin membebani generasi mendatang dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim.