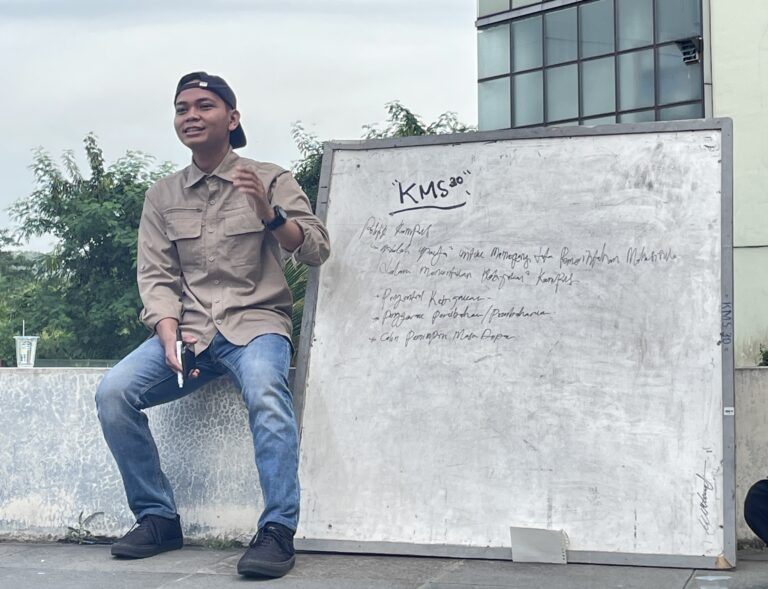Lagu Bella Ciao memang disenangi banyak kalangan—dari suporter bola, aktivis mahasiswa, kaum marjinal kota, hingga bocah gamers kesayangan orang tua. Tapi, pemaknaan kita terhadap suatu lagu sering kali tumbuh dari pengetahuan tentang kisah di balik nadanya. Musik, sebagaimana halnya simbol, tak pernah netral. Ia membawa jejak duka, sejarah, harapan, dan kadang wajah ideologis yang tak mudah terbaca.
Tahun 2021 lalu, Elseid Hysaj, bek asal Albania yang baru bergabung dengan Lazio, memperkenalkan dirinya kepada publik dengan menyanyikan lagu “Bella Ciao”. Ia menyanyikannya dengan semangat polos, mungkin karena sekadar iramanya enak atau viral di TikTok. Tapi apa daya, semangat yang ia tunjukkan justru menyalakan amarah Ultras Lazio. Protes bermunculan, bukan karena suara sumbangnya, tapi karena pilihan lagunya: “Bella Ciao” bukan sembarang nyanyian.
“Bella Ciao” adalah lagu perlawanan. Ia dinyanyikan oleh para Partisan—gerilyawan anti-fasis yang bertempur melawan rezim Benito Mussolini dan pendudukan Nazi Jerman di Italia. Dari hutan-hutan pegunungan hingga lorong-lorong kota, lagu ini menjadi semacam azan bagi perlawanan rakyat miskin dan buruh tani terhadap penindasan. Dan pasca-Perang Dunia II, lagu ini terus hidup dalam berbagai demonstrasi kiri, dinyanyikan di barikade dari Roma hingga Santiago.
Ultras Lazio sendiri dikenal sebagai kelompok suporter sayap kanan. Sebagian di antaranya bahkan terang-terangan menunjukkan simbol fasis, seperti salut Romawi dan swastika. Maka ketika Bella Ciao dikumandangkan oleh pemainnya sendiri, itu dianggap pengkhianatan identitas klub. Ironis memang, ketika sebuah klub sepak bola bisa mencerminkan ideologi politik tertentu, tapi itulah wajah sepak bola di Eropa.
Sebagai perbandingan, lihatlah rivalitas antara Lazio dan Livorno. Livorno, kota pelabuhan di Toscana, dikenal sebagai salah satu basis ideologi kiri paling kuat di Italia. Kota ini merupakan tempat kelahiran Partai Komunis Italia pada tahun 1921. Klub sepak bolanya, A.S. Livorno Calcio, memiliki basis suporter sayap kiri yang militan. Mereka tak ragu membawa bendera palu arit ke stadion, mengenakan kaus Che Guevara, menyanyikan lagu-lagu revolusioner, dan mengecam simbol-simbol fasis. Di sanalah lagu “Bella Ciao” tak hanya dinyanyikan, tapi menjadi napas perlawanan yang terus dijaga.
Rivalitas antara Lazio dan Livorno tak sekadar tentang si kulit bundar, tapi pertarungan dua dunia: dunia pekerja melawan dunia elite, rakyat tertindas melawan aparat status quo. Pertarungan itu menyala bukan hanya di lapangan, tapi juga di tribun, mural kota, dan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan dada bergemuruh.
Begitu pula di Skotlandia. Rivalitas Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers lebih dari sekadar derbi kota. Ia mewakili sejarah kolonialisme, agama, dan perlawanan. Celtic lahir dari komunitas Katolik Irlandia yang terpinggirkan di tanah Skotlandia, sementara Rangers mewakili Protestan Britania yang dominan. Setiap gol, setiap chant, membawa beban sejarah yang tak pernah selesai. Bahkan bendera yang dikibarkan pun bukan sekadar warna, tapi identitas yang membakar.
Di Turki, Galatasaray dan Fenerbahce pun mengusung cerita serupa. Galatasaray, lahir dari lingkaran elit Ottoman dan berakar pada kemapanan, sementara Fenerbahce mewakili kelas pekerja Istanbul sisi Asia. Rivalitas ini menegaskan satu hal: bahkan dalam hal hiburan massal seperti sepak bola, kelas tak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berganti bentuk dan kostum.
Begitulah sepak bola di Eropa, ia tak berdiri di ruang hampa. Ia tak steril dari politik, sejarah, bahkan agama. Justru karena itu, ia menjadi lebih dari sekadar permainan. Ia menjadi medan simbolik, tempat rakyat biasa menyuarakan perlawanan, atau tempat kaum elite mempertahankan hegemoninya.
Sayangnya, banyak dari kita menonton sepak bola hanya sebagai tontonan. Kita bersorak saat gol tercipta, marah saat wasit curang, tapi tak pernah menggali lebih dalam. Kita tak tahu bahwa nyanyian di tribun bisa jadi lebih radikal dari pidato di parlemen, bahwa mural suporter bisa lebih tajam dari tajuk utama koran.
Dan dari kasus Elseid Hysaj, kita belajar satu hal penting: pemaknaan atas simbol harus lahir dari kesadaran. Menyanyikan lagu perjuangan tanpa memahami sejarahnya bisa menjadi boomerang. Sebab di dunia yang sarat makna, ketidaktahuan bukanlah pembelaan.
Di Indonesia, barangkali belum sejelas itu pembelahan ideologis antar klub. Tapi bukan berarti kultur stadion kita steril. Potensinya besar. Terutama ketika suporter mulai sadar bahwa mereka bukan hanya konsumen tontonan, tapi bagian dari gerakan sosial. Ketika tribun bisa jadi ruang solidaritas, bukan hanya tempat umpatan.
Maka dari itu, jangan pernah anggap enteng sepak bola. Ia bisa menjadi cermin masyarakat. Dan jika ditarik dengan benang sejarah, ia bisa menjadi arena pertarungan yang lebih tajam dari debat politik. Stadion adalah barikade, dan para suporter adalah pasukan ideologis. Tinggal bagaimana kita memilih berdiri di sisi mana: di tribun sunyi yang hanya menonton drama, atau di tribun bersuara yang tahu untuk apa mereka bernyanyi dan bersuara.